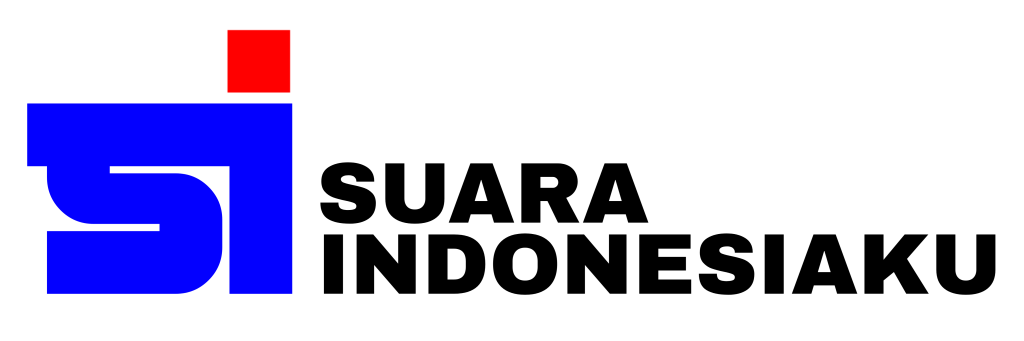Opini Oleh:
Dr. A. Hasdiansyah, M.Pd., M.A
Universitas Muhammadiyah Parepare
Suaraindonesiaku.com — Gelombang demonstrasi yang melanda beberapa kota dalam beberapa hari terakhir kembali memperlihatkan wajah buram bangsa ini. Jalanan yang dipenuhi massa berujung ricuh, gedung DPRD di Makassar hangus terbakar, sejumlah kantor pemerintah dirusak, bahkan kendaraan ikut jadi sasaran amarah. Di balik kobaran api, kita menyaksikan sesuatu yang jauh lebih serius: abu di hati rakyat yang telah lama menumpuk, kini ditiup angin ketidakadilan.
Kemarahan itu jelas bukan lahir dalam ruang hampa. Ia meledak dari rentetan kebijakan dan sikap penguasa yang semakin kehilangan empati. Ketika DPR secara vulgar mengusulkan penambahan tunjangan bagi anggotanya, publik hanya bisa mengernyit: di tengah ekonomi rakyat yang seret, wakil mereka justru sibuk menambah kenyamanan hidup sendiri. Padahal, gaji pokok anggota DPR “hanya” Rp 4,2 juta per bulan, tetapi tunjangan yang melekat bisa mencapai lebih dari Rp 60 juta—dari tunjangan kehormatan, komunikasi, rumah dinas, listrik, hingga perjalanan dinas (Tempo, 2024; Detik, 2024). Ironinya, gedung yang seharusnya menjadi simbol aspirasi rakyat malah terasa seperti menara gading. Jarak antara rakyat dan wakilnya bukan sekadar angka survei kepercayaan, tapi jurang yang makin dalam.
Di sisi lain, brutalitas aparat kembali menorehkan luka. Seorang pengemudi ojek online menjadi korban tabrakan polisi, yang hanya menambah panjang daftar peristiwa kelam aparat melawan warga sipil. Bukannya melindungi, mereka justru kerap melukai. Alih-alih menegakkan hukum, aparat tampil sebagai mesin kekerasan yang mematikan simpati. Namun, di tengah luka itu, rakyat sendiri sedang bergulat dengan kenyataan ekonomi yang kian menghimpit. Badan Pusat Statistik mencatat garis kemiskinan nasional pada Maret 2025 adalah Rp 609.160 per kapita per bulan, yang berarti rata-rata rumah tangga miskin (4,7 orang) hidup dengan pengeluaran di bawah sekitar Rp 2,88 juta per bulan Persentase penduduk miskin tercatat 8,47% atau sekitar 23,85 juta orang, meski merupakan angka terendah dalam dua dekade (Badan Pusat Statistik Indonesia). Ironisnya, walau ada penurunan kemiskinan di perdesaan, kemiskinan di perkotaan justru meningkat menjadi 6,73% dari sebelumnya 6,66%.
Kesenjangan ini memperlihatkan jurang yang nyata: rakyat berjuang dengan penghasilan terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, sementara wakil mereka menikmati fasilitas fantastis dari uang negara. Perbedaan yang mencolok inilah yang melahirkan ketidakpercayaan dan rasa ketidakadilan yang makin dalam. Rasa frustrasi itu kemudian tumpah ke jalan, mencari saluran ekspresi yang sering kali tidak tersedia dalam ruang politik formal.
Ironisnya, demonstrasi yang seharusnya menjadi katalis sosial justru kerap berakhir sebagai ledakan tanpa arah. Tanpa narasi ideologis dan platform gagasan yang kuat, amarah massa mudah berubah menjadi kerusuhan destruktif. Dalam situasi seperti itu, penguasa dengan gampang menstigma gerakan rakyat sebagai “anarki,” sambil tetap membiarkan akar persoalan—ketidakadilan struktural, tunjangan berlebihan, dan kultur represif tidak tersentuh.
Di titik ini kita menyaksikan krisis berlapis. Pertama, krisis keadilan, ketika penderitaan rakyat diabaikan sementara elit merayakan kemewahan. Kedua, krisis legitimasi, ketika Polri semakin dicurigai bukannya dihormati. Ketiga, krisis gerakan, ketika rakyat yang marah kehilangan arah sehingga energi politik mereka habis dalam kemarahan sesaat tanpa menghasilkan perubahan berarti.
Sialnya, pemerintah pusat pun tidak banyak memberi harapan. Alih-alih meredam ketegangan dengan kebijakan yang solutif, pemerintah lebih sering melontarkan pernyataan normatif. Dalam konteks kerusuhan, sikap diam seperti itu dipahami publik sebagai bentuk pembiaran. Sementara rakyat tahu, akar masalah adalah kesenjangan ekonomi, perilaku arogan DPR, hingga kekerasan aparat masih berdiri kokoh tanpa pembenahan. Ini tentu bukan pembenaran terhadap kerusuhan dan perusakan. Gedung yang terbakar memang bisa dibangun kembali, tetapi kerusakan kepercayaan publik jauh lebih sulit dipulihkan. Api di jalan hanyalah manifestasi amarah, bukan jawaban atas persoalan. Jika hanya dipadamkan dengan gas air mata dan barisan aparat, peredamannya pasti bersifat sementara, sementara bara ketidakadilan terus menggerogoti.
Untuk keluar dari lingkaran destruktif ini, dibutuhkan sinergi langkah konkret. Pertama, DPR harus menghentikan obsesi terhadap tunjangan. Sulit berharap rakyat percaya kepada wakilnya jika mereka justru sibuk menumpuk fasilitas. Kedua, Polri harus melakukan reformasi nyata: aparat mesti tampil sebagai pelindung, bukan penebar trauma. Kekerasan harus dibalas dengan sanksi tegas, bukan disembunyikan di balik seragam. Ketiga, pemerintah wajib memulihkan keadilan sosial, bukan sekadar dengan retorika, tetapi dengan tindakan nyata: menstabilkan harga kebutuhan pokok, melindungi pekerja informal seperti ojol, dan memastikan layanan publik yang bermartabat.
Masyarakat sipil juga punya peran penting. Dialog sosial dan gerakan publik harus diarahkan kembali ke jalan gagasan, bukan sekadar ledakan emosi. Gerakan yang berangkat dari visi, ideologi, dan narasi yang jelaslah yang dapat menyalakan perubahan sistemik, bukan sekadar meninggalkan bara kerusuhan. Api mungkin bisa membakar gedung, tetapi hanya gagasan yang dapat membakar kesadaran dan memaksa sistem berubah. Jika energi rakyat dialihkan menjadi gerakan intelektual yang terarah, penguasa tak lagi bisa bersembunyi di balik kursi empuk atau seragam aparat.
Hari-hari ini kita belajar satu hal penting: bangsa ini tidak kekurangan amarah, melainkan kekurangan arah. Jika api jalanan terus dipadamkan tanpa menyentuh bara di hati rakyat yang hidup dengan segala kekurangan sementara wakilnya menerima puluhan juta rupiah, maka cepat atau lambat abu itu akan ditiup angin sejarah. Dan ketika api berikutnya menyala, ia bisa lebih besar, lebih sulit dipadamkan, dan mungkin membakar lebih dari sekadar gedung.